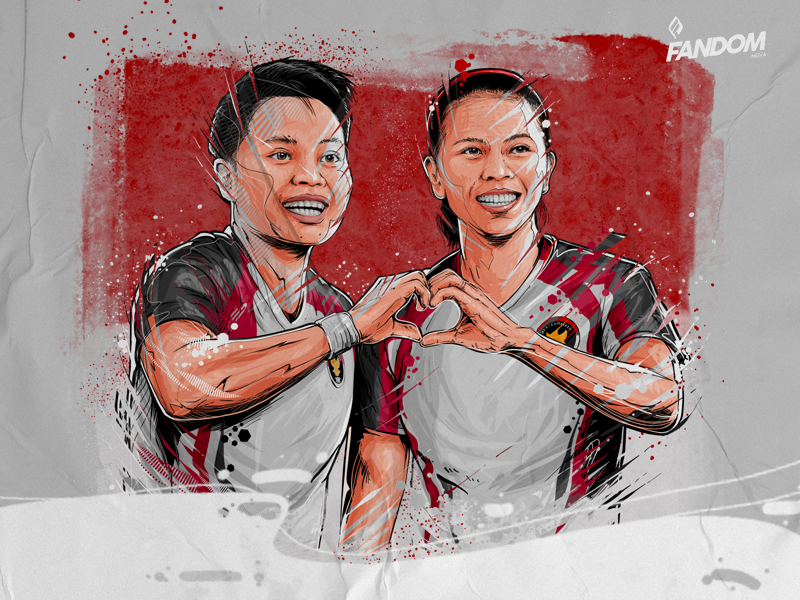Perdebatan yang kembali muncul paska kejayaan Portugal yang menjuarai Piala Eropa 2016 dengan hanya sekali (ketika bersua Wales) memenangi pertandingan dalam waktu normal 90 menit adalah kepantasan sebuah gaya dalam memainkan sepak bola dan korelasinya dengan kapabilitas untuk juara.
Jadi untuk mendedah dari awal, kalian (kamu, juga saya) perlu belajar untuk paham terlebih dahulu satu hal penting bahwa bukan urusan kita untuk mencemooh gaya bermain sepak bola tiap pelatih di tiap-tiap kesebelasan sepak bola, baik di klub ataupun timnas.
Mengkritik boleh, ya minimal untuk mengekspresikan bahwa kita kerapkali mengantuk melihat sepak bola bertahan yang dewasa ini dijadikan pujaan banyak orang.
Masalahnya bukan soal menjadi moralis atau pragmatis dalam menikmati sepak bola, lagipula, prestasi sebuah timnas atau sebuah klub sepak bola kerapkali tidak berimbas apapun terhadap kehidupan kita.
Misal, ketika musim depan Tony Pulis menjuarai Liga Primer Inggris dengan gaya sepak bolanya yang seperti rugby itu, apa implikasinya ke hidup saya? Apakah Portugal yang juara dengan kolektivitas ala Fernando Santos dan permainan bertahan selama fase gugur akan membantu saya lulus skripsi? Tentu saja tidak.
Itulah kenapa, perdebatan dan saling ejek di linimasa media daring perihal sepak bola baik atau buruk sama sekali tidak membantu. Tentu lebih asyik menukil kisah Portugal dan Fernando Santos dengan cara Zen RS yang menganalogikannya dengan karya sastra Fernando Pessoa.
Atau misal, Anda coba mencari efek dari kemunculan Jose Mourinho terhadap perkembangan taktikal di sepak bola modern. Itu lebih membantu mencerdaskan pikiran kita dan membantu kita menjadi lebih open minded tentang sepak bola.
Langkah selajutnya, kita harus paham tentang efek lain dari perkembangan taktikal akibat dari permainan pragmatis. Mari mundur ke beberapa tahun ke belakang ketika pria yang kini berkepala botak, mentas dari tim yunior Barcelona dan membuka mata sepak bola dunia dengan permainan yang memukau.
Pep Guardiola, nama pria plontos itu, membuktikan kepada publik bahwa memainkan dan menjadi juara dalam sepak bola dengan cara yang agung dan mewah adalah mungkin, bukan hanya isapan jembol belaka seperti yang kerap didengungkan loyalis Arsene Wenger.
Masalahnya, Pep, yang menjadi simbol keseksian sepak bola lewat kemampuan taktikalnya yang inovatif itu, mengalami resistansi berarti dari beberapa nama yang di kemudian hari terbukti mampu menandingi sepak bola rancak ala Catalan dengan cara main yang berbeda 180 derajat dengan gaya Pep.
Ia dihancurkan Jose Mourinho dan Inter Milan yang memainkan sembilan sampai sepuluh pemain di belakang dan menyulap Samuel Eto’o menjadi seorang bek kiri dalam satu pertandingan.
Pep juga dipecundangi Jupp Heynckes dengan sepak bola ala Bavaria yang kuat, terorganisir, dan tajam dengan sayap magisnya dalam diri Arjen Robben dan Franck Ribery. Andai masih kurang, di musim terakhirnya bersama Bayern Munchen musim lalu, karier Pep di Eropa diakhiri dengan tragis oleh kuatnya tembok Atletico Madrid yang dibangun El Colo, Diego Simeone.
Apakah ini senjakala Pep Guardiola? Tentu saja tidak, walau untuk mengakui bahwa dalam tiga sampai empat tahun terakhir, perkembangan sepak bola secara taktikal makin kompleks dan memainkan sepak bola pragmatis kerapkali menjadi solusi terbaik.
Mudahnya saja, banyak beberapa klub dan timnas mulai tidak nyaman memainkan bola dan menguasainya selama mungkin untuk membuat peluang, menyerang lawan atau mencetak gol sebanyak mungkin.
Orang berlomba-lomba untuk seminim mungkin menguasai bola dan seminim mungkin memainkan sepak bola penuh resiko yang takut kebobolan atau takut kalah. Tentu tidak bisa disalahkan karena dua hal.
Pertama, kita tidak pernah tahu tuntutan yang dibebankan kepada seorang pelatih. Misal, kita tidak tahu nasib Tony Pulis jikalau ia memainkan sepak bola terbuka dengan skuat West Bromwich Albion yang semenjana itu dan berujung degradasi.
Kedua, seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh beberapa pakar, tidak semua klub atau negara memiliki takdir dan sumber daya dana yang tak terbatas untuk memiliki atau membeli pemain kualitas premium yang piawai menguasai bola dan mendikte permainan.
Sebagai contoh, apa salah Portugal jika kemudian pemain seperti Toni Kroos dan Mesut Ozil terlahir membela timnas Jerman dan bukan Portugal?
Maksud saya, ada beberapa hal di luar kuasa kita yang seharusnya mampu menjadi excuse bahwa beberapa pelatih memang terpaksa bermain pragmatis karena ia tak didukung oleh skuat yang mumpuni dan sumber daya yang terbatas.
Dan karena kompleksnya beberapa hal seperti saya bahas di atas, akan banyak tim yang ingin menjadi seperti Portugal nantinya. Ini yang lebih saya takutkan, karena jujur, hanya sekali saya terhibur menyaksikan Portugal bermain selama Euro lalu dan itupun untuk laga yang berkesudahan dengan skor 3-3 kontra Hungaria.
Sama seperti efek Pep di Barcelona dulu, efek sepak bola pragmatis juga nanti akan menjadi tren yang populer. Di periode yang sama dengan kedigdayaan Pep Guardiola di Barcelona, timnas Spanyol juga aktif memainkan umpan-umpan pendek dan permutasi posisi yang yahud untuk menguasai Eropa dan dunia selama periode 2008-2012.
Tapi zaman berganti, karena di Piala Dunia terakhir, magis Iberia yang cantik dan seksi ala Spanyol sudah digantikan oleh kekuatan sistematis Jerman yang canggih dan modern.
Di Piala Eropa terbaru lalu bahkan, magis Iberia yang rupawan justru kandas oleh benteng-benteng kasar dan tangguh ala Italia dan si Iberia yang buruk rupa (re: Portugal) justru menjadi juaranya.
Sepak bola tidak pernah berhenti berevolusi. Baik secara bisnis (efek China’s Megatrends di sepak bola Tiongkok), secara finansial (Bung, gaji Graziano Pelle di liga Tiongkok lebih besar dari gaji Cristiano Ronaldo!) hingga secara taktikal.
Dan satu yang terpenting, sepak bola akan selalu mengejutkan. Dan coba bayangkan dan resapi baik-baik, dengan pola yang diatur UEFA untuk Piala Eropa 2020 nanti, jangan heran kalau negara semenjana seperti Kepulauan Faroe dan San Marino akan bersaing dengan Spanyol, Italia bahkan Jerman di putaran final.
Dan jangan sekalipun Anda mencaci San Marino kalau ia (nantinya) bermain parkir bus selama turnamen, karena yang Anda lakukan itu….jahat.
Kita perlu adil sejak dalam pikiran mengenai sepak bola dan perkembangan taktikalnya yang revolusioner. Yang tetap memuja sepak bola pragmatis, bisa menikmati bagaimana timnya bertahan dan mengkreasi peluang dengan serangan balik cepat yang tajam.
Bagi para moralis, bisa menyingkirkan sakit kepala karena sepak bola bertahan dengan masih menyaksikan tim-tim seperti Bayern Munchen yang akan ditangani Carlo Ancelotti, Barcelona yang masih bermain cantik bersama trio superhuman Amerika Latinnya, atau menanti seperti apa Manchester City di tangan si botak Pep Guardiola.
Karena bagimu sepak bolamu, bagiku sepak bolaku, Lakum Diinukum wa Liya Diin.